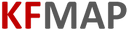Permukiman Kumuh di Jantung Kota: Mengurai Fenomena di Balik Rel Kereta
Permukiman kumuh di kawasan perkotaan masih menjadi persoalan yang kompleks. Hasil proyeksi BPS menunjukkan, pada tahun 2025, sekitar 60% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan dan angka ini diperkirakan naik menjadi 66,6% pada 2035. Banyak penduduk desa bermigrasi ke kota, dengan harapan meningkatkan kualitas hidupnya, karena peluang ekonomi dan fasilitas yang dianggap lebih baik.
Namun, kenyataannya tidak selalu demikian, dengan persaingan kerja yang ketat dan harga hunian yang tinggi membuat mereka terpaksa tinggal di lingkungan padat, serta tidak layak huni di pinggiran atau sela-sela pusat kota.
Permukiman kumuh di Indonesia secara hukum diatur melalui UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pada pasal 13 didefinisikannya permukiman kumuh sebagai permukiman tidak layak huni akibat ketidakteraturan bangunan, tingginya tingkat kepadatan, dan kualitas bangunan serta sarana-prasarana yang tidak memenuhi syarat.
Definisi tersebut dipertegas melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018, yang menyoroti prasarana lingkungan yang tidak memadai, seperti jalan, drainase, pengelolaan limbah, serta proteksi kebakaran. Indikator lain, seperti keterbatasan aksesibilitas, minimnya ruang terbuka, dan legalitas lahan yang belum jelas juga menggambarkan permukiman kumuh.
Jika dilihat dari teori pola perkotaan, fenomena permukiman kumuh sangat erat kaitannya dengan lokasi yang dekat pusat kegiatan dan jalur transportasi, seperti rel kereta. Teori Sektor Hoyt (1939) menjelaskan, bahwa kota berkembang mengikuti koridor transportasi dan sektor di sekitarnya cenderung menjadi hunian kelas pekerja, karena akses yang mudah ke pusat kota.
Faktor ekonomi, sosial, dan sejarah pun turut menjadi penyebab, seperti di sepanjang rel kereta dengan harga lahan yang murah akibat polusi dan kebisingan, dekat dengan lapangan kerja sektor informal, serta sejarah pembangunan rel di era kolonial yang memang diarahkan ke kawasan industri dan pelabuhan.
Kondisi ini dapat dilihat nyata di berbagai kota di Indonesia. Misalnya di Jakarta, permukiman padat banyak ditemukan di sekitar Stasiun KRL Manggarai, Tanah Abang, dan Kampung Bandan. Yogyakarta juga memiliki kampung padat di sekitar Stasiun Lempuyangan. Polanya konsisten, yakni dekat pusat kegiatan atau tempat kerja, dekat infrastruktur transportasi, dan harga lahan yang rendah.
Penanganan fenomena ini tidak hanya melalui relokasi, tetapi dapat dilakukan dengan perbaikan in-situ, penataan ulang lahan, hunian vertikal berbasis komunitas, dan pemberdayaan warga. Diperlukannya kolaborasi pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat agar dapat mewujudkan revitalisasi permukiman yang berkelanjutan.
Penulis: Ratih Putri Salsabila
Sumber:
https://kfmap.asia/blog/menata-kampung-melalui-praktik-akupunktur-perkotaan-di-mrican-yogyakarta/4170
https://www.bps.go.id/
https://bphn.go.id/
https://perkim.id/
https://journal.cicofficial.com/
https://www.netralnews.com/