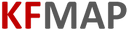Mengenal Tanah Partikelir, Latar Belakangnya dan Mengapa Dihapuskan?
Tanah partikelir didefinisikan sebagai suatu bidang tanah yang kepemilikannya dimiliki oleh “tuan tanah”, berasal dari Belanda atau pihak asing lainnya. Tanah partikelir bersifat eigendom, yaitu hak milik individu tertinggi berdasarkan sistem hukum tanah barat.
Tanah partikelir ini ditujukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak swasta untuk keperluan perolehan pendapatan. Namun, tidak seperti praktik jual-beli tanah pada umumnya, tanah partikelir memiliki sifat dan corak istimewa yang memberikan pemiliknya kewenangan eksklusif, akses ke wilayah dan sumber daya manusia, bahkan memberlakukan pajak.
Dalam sistem pertanahan terdahulu, penguasaan atas tanah partikelir ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu tanah usaha dan tanah kongsi.
Tanah usaha adalah tanah yang tidak dikuasai langsung oleh tuan tanah, melainkan tanah desa atau milik masyarakat adat dan bersifat turun-menurun. Sedangkan tanah kongsi adalah tanah yang dikuasai oleh tuan tanah secara langsung dan apabila terdapat usaha atau perumahan rakyat, maka akan diterapkan konsep sewa.
Munculnya kebijakan mengenai tanah partikelir bermula sejak tahun 1680-an era kongsi dagang Belanda (VOC) dan semakin masif kepemilikannya pada era kolonial Belanda (1808-1811) dengan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Herman Willem Daendels yang memperjualbelikan tanah-tanah partikelir kepada pihak ketiga sebagai “tuan tanah” dan memiliki hak-hak pertuanan.
Dalam buku Pertahanan, Agraria, dan Tata Ruang oleh Waskito & Hadi Arwono, hak-hak pertuanan dari pemilik tanah partikelir tersebut antara lain:
- Hak untuk mengangkat dan mengesahkan pemilihan, serta memberhentikan kepala-kepala kampung/desa dan kepala-kepala umum.
- Hak untuk menuntut kerja paksa atau memungut uang pengganti kerja paksa dari penduduk.
- Hak untuk mengadakan pungutan-pungutan berupa uang atau hasil tanah dari penduduk.
- Hak untuk mendirikan pasar-pasar dan memungut biaya pemakaian jalan dan penyebrangan.
Hak-hak pertuanan tersebut mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat, khususnya para petani, karena sumber daya dan tanah mereka telah dieksploitasi secara intensif dan semena-mena oleh para tuan tanah. Hal ini memicu berbagai protes dan kerusuhan yang mendorong penghapusan tanah partikelir.
Saat ini, Indonesia telah meraih kemerdekaannya sejak tahun 1945. Lalu, bagaimanakah nasib dari tanah-tanah partikelir peninggalan kolonial Belanda tersebut?
Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya, pemerintah menghapus status tanah partikelir, diantaranya karena dianggap bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), melalui Undang-Undang (UU) No. 1/1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir dan Undang-Undang (UU) No. 5/1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Pemerintah Indonesia telah melakukan kebijakan reforma agraria dengan mengambil alih lahan milik pihak asing ke tangan rakyat dan negara melalui sistem ganti-rugi untuk meminimalisir potensi konflik. Dengan pemberlakuan kebijakan tersebut, rakyat Indonesia yang masih memiliki tanah partikelir akan diubah status kepemilikan tanahnya menjadi hak milik apabila memenuhi persyaratan.
Sementara itu, tanah partikelir yang dimiliki oleh pihak asing tidak diperkenankan mengantongi hak milik, dan tanahnya akan terhapus serta menjadi milik negara.
Penulis: Adhika Wisnu Aryo Putro Wibowo
Sumber:
https://kfmap.asia/blog/apa-itu-tanah-partikelir/2994
https://books.google.com/
https://detik.com/
https://e-journal.unair.ac.id/
https://hukumonline.com/
https://kompas.com/
https://peraturan.bpk.go.id/